Tetiba saya mendapat kenalan baru. Semalam ada pesan WhatsApp masuk ke ponsel saya. Pukul 20.06. Dari nomor yang saya tidak kenal. Hanya sepenggal kalimat salam. Tidak saya balas. Sengaja. Saya menunggu pesan berikutnya.
Sampai pagi saya sudah dan masih melupakan salam yang belum saya jawab itu. Simpulan sementara, salam salah alamat. Atau ulah iseng belaka. Atau ... salah seorang mantan lagi kumat kangennya?
Saya berangkat seperti biasanya. Pukul 06.15 sidik jari saya sudah teridentifikasi oleh mesin presensi. Pukul 06.36 ada notifikasi pesan masuk. Harus segera saya buka dan balas. Istri saya mengabarkan, dia sudah sampai di tempat kerja. Usai membalas pesan istri, saya tutup lagi layar ponsel.
Selang lima menit kemudian ada pesan masuk lagi. Dari nomor yang belum saya simpan dengan nama. Ini sebagian isinya.
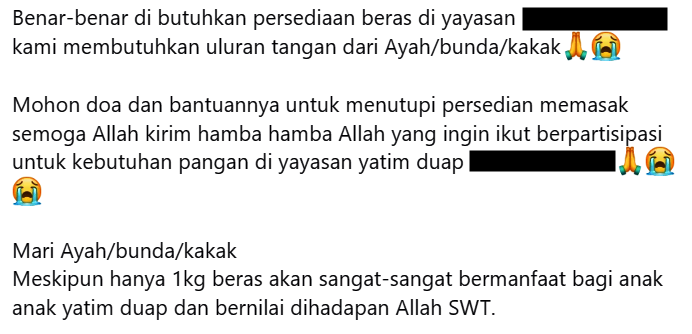
Ups, dari nomor yang semalam berkirim salam. Yayasan pengelola panti asuhan rupanya. Membuka ladang amal saleh. Tersanjung saya demi mendapat undangan untuk turut "bercocok tanam" di ladang itu. Sayangnya, saya belum kapok menjadi orang pelit. Bukannya mengingat-ingat berapa digit saldo di rekening tabungan dan berapa lembar berwarna apa yang menghuni dompet, saya justru menikmati tarian protes yang berlenggak-lenggok binal di kepala saya.
Apa yang dimaui yayasan ini? Menyantuni anak yatim dan duafa atau melecehkan mereka? Kalau hendak menyantuni, semestinya yayasan menjaga muruah kaum papa itu. Bukan sebaliknya, menjual kenestapaan mereka.
Undangan untuk mengulurkan tangan itu diikuti dua keping video pendek. Di menit yang sama. Dua-duanya menayangkan situasi panti. Video pertama menampilkan seorang pria muda tengah ngaru (mengaduk beras setengah matang). Disertai takarir: "Makan sama lauk pauk jarang mereka rasakan//kalau tidak punya uang hanya makan nasi tambah garam//kadang sama kangkung yang tumbuh liar//kadang juga minta lalap di kebun ustad//jika ada yg ngasih lauk pauk yang enak mereka sangat bahagia//seringkali kita di anggap pengemis//Karena selalu menawarkan program santunan Yatim Dhuafa//(ditutup dengan kutipan sabda Nabi mulia.)" *)
Video kedua dibuka dengan tayangan wajah asrama yang kumuh. Jemuran pakaian bergelantungan di depan kamar-kamar lantai 1 dan di bibir jendela-jendela lantai 2. Scenes berikutnya didominasi adegan anak-anak nyadhong jatah makan. Masing-masing memegang piring plastik. Seseorang, mungkin pengasuh panti, menuangkan nasi ke piring-piring itu. Ditakar dengan mangkuk plastik. Satu mangkuk penuh untuk tiap-tiap piring yang disodorkan dari luar jendela.
Salah seorang anak memamerkan piringnya yang sudah terisi gunungan nasi tanpa lauk ataupun sayur. Senyumnya mengembang. Lalu seorang anak yang lain makan di tempat yang kurang bersih. Muluk dan ngemplok nasi tanpa lauk. Gerakan tangannya lamban. Tanpa gairah. Pandangannya menunduk ke piring aluminium yang dipegang dengan tangan kirinya.
Disusul flyer. Masih di menit yang sama: 06.41.

Kiriman empat pesan—satu teks, dua video, dan satu gambar—itu belum mampu menggugah minat saya untuk menanggapi. Hingga menyusul pesan berikutnya. Pukul 08.45. Teks agak panjang. Lebih sopan. Pemegang nomor WhatsApp memperkenalkan diri. Menyebut nama. Mengaku sebagai relawan panti. Nama panti dan yayasannya disebut. Wow, ... lintas provinsi! Mengungkapkan maksudnya. Kali ini rayuannya lebih lugas.
Saya balas singkat, "Silakan hubungi ... (saya menyebut nama sebuah lembaga amil zakat berskala nasional) setempat."
Tidak ada balasan balik. Barangkali jawaban saya itu sudah cukup memuaskan keperluannya.
Sebetulnya saya bisa menjawab secara basa-basi. Minta maaf karena belum bisa berpartisipasi. Lalu merangkai untaian doa indah memesona. Puitis. Magis. Namun, itu sama sekali bukan solusi. Frasa "mohon doa" yang mengawali salah satu kalimat yang saya terima itu saya identikkan dengan kalimat yang lazim ditulis pada undangan pesta perkawinan itu.
Saya jadi berandai-andai. Imajinasi saya berkelana liar.
Saya membuat yayasan. Berlabel lembaga kesejahteraan sosial. Pinjam bangunan kosong. Milik perseorangan, organisasi partikelir, atau pemerintah. Yang penting boleh dipinjam. Bukan disewa. Menampung anak-anak yatim, telantar, atau duafa. Memasang papan nama "Panti Asuhan Anu". Menyebarkan proposal permohonan derma. Kepada perseorangan, organisasi sosial, organisasi politik, instansi pemerintah, dunia usaha dan industri. Tidak terlewatkan, lembaga-lembaga fundraising. Dengan berbagai media. Lewat aneka saluran informasi. Konvensional dan digital.
Saya yakin bisa mendulang kepercayaan dari beragam entitas itu. Dana mengalir deras ke rekening yayasan. Setiap bulan. Tinggal mengatur arus belanja. Agar isi rekening tidak terkuras habis untuk biaya operasional panti. Akhir tahun membuat proposal baru: pengadaan asrama. Kebutuhan tanah, bangunan, dan segenap sarana/prasarana bisa dikalkulasi. Dasar penghitungannya, jumlah anak asuh yang terdaftar di buku induk panti. Yang penting terdaftar. Bisa riil, bisa fiktif.
Tanah dan bangunan terealisasi. Saya sisihkan sebagian untuk tempat usaha. Usaha apa saja. Yang penting bisa menjadi penanda bahwa di situ ada kegiatan ekonomi. Tenaga kerja sudah tersedia: anak-anak panti. Modal diambil dari saldo tabungan yayasan. Kalau kurang—dan mesti dinyatakan kurang—tinggal membuat proposal lagi.
Muncul masalah baru. Anak-anak sering diundang ke berbagai acara. Oleh para donatur, perseorangan maupun institusi. Mulai dari tasyakuran ulang tahun, selamatan orang meninggal, selamatan menjelang pernikahan, selamatan peresmian gedung, selamatan pembukaan cabang usaha, atau apa pun. Lebih-lebih dalam bulan Muharam, lebarannya anak yatim.
Untuk mengangkut anak-anak, yayasan harus menyewa mobil. Makin sering mengantar anak-anak keluar, makin besar dana yayasan tersedot. Sebenarnya masih untung. Total uang saku yang kami terima dari sahibulhajat lebih besar daripada ongkos sewa angkutan. Akan tetapi, tentu lebih praktis kalau panti punya mobil sendiri. Ah, apa susahnya bikin proposal pengadaan mobil? Para donatur pasti juga lebih senang kalau kami ke mana-mana naik mobil inventaris panti.
Anak-anak tinggal di asrama dengan fasilitas relatif memadai. Mobil operasional siap membawa mereka memenuhi undangan para donatur. Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah mereka pegang. Anak-anak bisa berobat dan bersekolah secara cuma-cuma. Bantuan sembako silih berganti dikirim ke panti. Pakaian seragam sekolah, harian, dan kostum hari raya hampir tidak pernah perlu dibeli. Donasi pakaian baru atau bekas pantas pakai tidak pernah terlambat. Unit usaha sudah bisa dirasakan manfaatnya, menambah pemasukan. Sedekah rutin bulanan dan insidental masih lancar mengalir ke kas panti. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang masih layak untuk didustakan?
Sebagai pengurus sekaligus pengasuh, tentu sah-sah saja saya ikut menikmati kesejahteraan anak-anak asuh dan kemakmuran panti. Atas nama pengasuh, saya pantas ikut tinggal di asrama—tanpa harus susah payah membangun rumah sendiri. Selama tidak ada acara yang mengundang anak-anak, saya leluasa memakai mobil panti untuk keperluan apa pun. Untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga, saya cukup mendompleng anak-anak. Masa, koki panti harus memasak terpisah untuk keluarganya? Ketika mengantar anak-anak ke acara tasyakuran, biasanya saya didaulat sebagai penceramah. Setidaknya, dipercaya untuk memimpin doa bersama. Lumayan, berbekal hafalan beberapa potongan ayat suci dan rangkaian doa ala kadarnya, kiranya layak saya menerima amplop lebih tebal daripada uang saku untuk anak-anak.
Kian lama panti kian makmur. Para penghuninya, tak terkecuali—untuk tidak menyebut terutama—pengasuh cum pengurusnya, kian sejahtera. Namun, kemakmuran dan kesejahteraan itu tidak boleh mencolok ke permukaan. Panti asuhan mesti tampil memprihatinkan. Anak-anak harus pandai mengundang iba. Namun, anak-anak umumnya susah berakting. Agar tampak memelas, tidak ada cara lain. Mereka harus dibuat nelangsa beneran.
Makan enak seminggu sekali saja sudah lebih dari cukup bagi mereka. Hari-hari lainnya cukup dicatu nasi polos. Tanpa lauk dan sayur. Atau sesekali dengan sambal korek plus lalap kukusan sayur limbah, sedekah dari tukang sayur keliling. Sekali tempo menu makan khas panti itu dipotret atau divideokan. Lalu diviralkan lewat media sosial. Itu jurus sakti untuk mengundang donasi agar datang bertubi-tubi.
Anak-anak makan asal kenyang saja. Pengasuh dan keluarganya tetap bisa menyantap menu yang berbeda. Toh anak-anak tidak bakal berani mengintip meja makan keluarga pengasuh. Petunjuk kitab suci cukuplah ampuh untuk doktrin etika tentang itu.
Wow, ... seru juga mengkhayalkan peran sebagai manajer panti asuhan ini! Pengasuh anak yatim dan duafa. Begitu mulia sebutan itu! Di balik citra mulia secara spiritual itu, diam-diam saya menikmati kemuliaan di ranah lain: kemuliaan duniawi. Berkat kepekaan sense of marketing saya. Rupanya, kenestapaan bisa menjadi komoditas yang laku keras. Dengan menjual kenestapaan kaum papa, saya bisa meraup laba berlipat ganda.
Imajinasi saya kehabisan amunisi. Mesin khayalan mendadak mati. Tinggal tersisa satu pertanyaan mengganjal: apakah menjual kenestapaan kaum papa itu tidak lebih kejam daripada menghardik dan menelantarkan mereka?
Tetiba saya kehilangan nyali untuk melanjutkan khayalan ini. Apalagi untuk mewujudkannya.
Tabik.
*) Disalin sebagaimana tulisan aslinya, tanpa penyuntingan ejaan.





Tidak ada komentar:
Posting Komentar