 |
| Patung sepasang dewa-dewi di tengah-tengah kolam ikan (Sumber foto: Anggara Wikan Prasetya/travel.kompas.com) |
“Pyenengan daleme Sumur, Bu (rumah Anda di Dusun
Sumur, Bu)?” tanya saya kepada wanita yang sedang memetik daun kemangi di
sebelah gazebo tempat kami rehat.
Yang saya tanya mengiakan. Kemudian saya menanyakan tahun kelahirannya. Enam tahun lebih muda daripada saya. Saya kecewa. Dengan selisih 6 tahun, dijamin kami tidak pernah bertemu sebelumnya. Lebih mengecewakan lagi, ternyata dia bukan pribumi. Daerah asalnya Sragen. Suaminya, yang asli Sumur.
Sayang, saya tidak menanyakan nama suaminya. Bisa jadi, kami
saling mengenal. Atau, setidaknya saya mengenalnya. Atau sebaliknya, ia yang
masih ingat saya. Anak-anak dusun Sumur pasti se-SD dengan saya: SD Negeri Suci
I (sekarang SD Negeri 1 Suci). Kalau tahun masuknya selisih (-3) hingga (+3)
tahun, biasanya saya masih ingat—setidaknya namanya.
Meski bernama Sumur, dusun ini tergolong kering. Mungkin malah
tidak ada satu pun sumur air di sana. Tanahnya tandus. Pertaniannya didominasi
budi daya palawija. Kalaupun ada yang menanam padi, hanya gaga rancah. Sebagian
besar lahannya berupa lereng pergunungan kapur. Pada musim hujan, petak-petak
tanah sempit di sela-sela gugusan batu kapur itu ditumbuhi kacang tanah, kedelai,
jagung, sorgum atau cantel, atau singkong.
Di puncak musim kemarau, yang tersisa tinggal pohon-pohon
keras yang berdiri kaku tanpa daun. Jati, mahoni, dan akasia kompak meranggas demi
menampakkan gugusan batu berpori, material pembentuk bentangan “candi alami”.
Panorama khas di sepanjang Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunung Sewu.
Kondisi alam yang gersang itu membuat saya sangsi ketika tersiar
kabar adanya perkebunan alpukat di Sumur, sekitar 3 tahun lalu. Lebih
mengejutkan lagi, kebun di perbukitan kapur itu mendadak viral sebagai
destinasi wisata. Saya jadi penasaran, yang dikembangkan itu kebun buah atau
taman rekreasi? Atau dua-duanya, agrowisata? Penasaran berikutnya, siapa
bosnya: “sultan” lokal atau konglomerat asing?
Setelah tertunda sekian lama, akhirnya kesampaian juga
keinginan saya untuk menengok “keajaiban” di tetangga desa kelahiran saya itu. Dalam
perjalanan kembali dari Pantai Srau, Ahad, 8 Juni 2025, saya dan rombongan
mampir sejenak di Gunung Dewa Dewi (GD2). Bagi saya, kunjungan ini kelewat
telat. Letaknya hanya 2—3 km di sebelah timur dusun kelahiran saya. Tiap-tiap 1—2
bulan saya pulang kampung. Eh, mudik. Belum pulang kampung—menurut definisi
siapa itu. Hanya 1 atau 2 malam. Sekadar mengempeng Simbok.
Setahun silam hampir kesampaian. Mumpung ada nunutan
mobil. Tetangga di Semarang—satu keluarga—mengantar keluarga saya (minus saya)
mudik. Mereka menginap semalam di rumah suwung kami. Paginya kami piknik, tanpa
bekal makanan karena 1 hari lagi baru Lebaran. Anak gadis tetangga saya itu mengajak
ke pantai. Saya tawarkan sekalian mampir di kebun alpukat. Mantunya Simbok
tidak tertarik. Ya, sudah. Kali lain saja, pas mudik tanpa anaknya mertua.
Ternyata dendam saya baru terlampiaskan setahun lebih berikutnya.
Semula saya menjadwalkan kunjungan ke GD2 sebagai destinasi pertama, Sabtu pagi.
Kepada teman-teman, saya menjanjikan suasana matahari terbit di puncak bukit
alpukat. Gagal! Selepas subuh, Mbakyu pembarap telanjur menyeduh kopi untuk
kami. Kami tidak tega untuk menyia-nyiakan. Takut kualat.
Sesampai di parkiran, saya berpesan kepada teman-teman, “Di
sini, tujuan utamanya bukan menikmati pemandangannya. Melainkan, mempelajari
manajemen perubahannya.”
Bagi saya, kehadiran kebun alpukat di perbukitan kapur
Sumur-Nujo itu cukup memantik perhatian. Ya, perbukitan yang menjadi lahan
perkebunan itu irisan dua dusun: Sumur (Desa Suci) dan Nujo (Desa Gambirmanis).
Saya—mungkin juga kebanyakan masyarakat sekitar lokasi GD2—tidak pernah
membayangkan sebelumnya bahwa pohon alpukat mau hidup di sana. Faktanya, bisa.
Tanaman buah itu sekarang rata-rata sudah mencapai ketinggian lebih dari 2 meter. Sebagian sudah mulai berbuah.
Tanaman yang setahu saya menyukai hawa sejuk itu dibudidayakan langsung
dalam skala besar. Konon tahap pertama disiapkan lahan 47 hektare. Kalau gagal,
pasti investornya menanggung kerugian cukup besar. Harga tanahnya barangkali
tidak seberapa. Masyarakat di sana belum melek bisnis tanah. Namun, modifikasi
lahannya tentu menguras modal. Semua galengan tampak baru. Berarti, galengan
lama—alami maupun buatan—dibongkar. Tanah di petak-petak lahan penanaman
alpukat diratakan. Setahu dan seingat saya, lazimnya petani tradisional
setempat membiarkan lahan bercocok tanam di lereng perbukitan seperti itu tetap
miring.
Pemodal itu tentu tidak sedang berspekulasi. Konversi lahan
itu pasti sudah melalui riset. Teknologi pertanian dilibatkan. Rekayasa cuaca,
bahkan, mungkin juga dilakukan. Sejauh ini, pertumbuhan pohon-pohon alpukat itu
cukup menggembirakan. Dari kejauhan tampak hijau merata. Dari dekat tampak
subur segar. Apalagi, beberapa sudah berbuah. Harapan panen layak untuk
dikantongi.
Bahkan, sebelum panen buah alpukat, panen wisatawan sudah
dapat dinikmati. Sejak Lebaran yang lalu pengelola mulai menerapkan tarif tiket
masuk. Sebelumnya, pengunjung hanya dikenai ongkos parkir. Kabarnya, parkir
kendaraan itu dikelola oleh karang taruna setempat.
Pelibatan penduduk lokal itu menjadi nilai plus. Ketika
bersambang ke sana tempo hari, saya tidak menemukan wajah asing. Semua petugas
saya kenali sebagai warga setempat. Para penjaga loket tiket masuk dan portal jalan
keluar—walaupun berkostum ala orang kota—saya pastikan muda-mudi setempat.
Logat Praci pegunungan masih kental pada bahasa mereka. Karakter “ndesa”
juga masih kentara pada orang-orang yang terlibat dalam operasionalisasi GD2. Ongkos
naik jip keliling area perkebunan hanya dibanderol 150 ribu per trip. “Pak
Ogah” yang memandu arah dan arus kendaraan pengunjung di dua pertigaan—masuk dan
keluar area—tidak menodongkan ember ataupun besek kepada pengendara.
Pemberdayaan masyarakat lokal itu tercantum eksplisit di
papan manifesto bisnis GD2. Ya, dalam perjalanan kembali ke tempat parkir, saya
mendapati plang proyek. Papan yang sepasang tiangnya tertancap ke tanah bercampur
batu putih kekuningan itu memuat sejumlah butir manifesto. Salah satunya,
SDM-nya warga lokal. Wanita pemetik daun kemangi itu juga bekerja di resto yang
berdiri di puncak salah satu bukit lahan perkebunan alpukat. Saya menduga, tenaga
kerja resto itu—meski menunya kekinian—didominasi warga lokal. Barangkali hanya
jajaran manajemen dan dietisien yang diisi orang luar.
Di manifesto juga tercantum bahwa modal usaha murni berasal
dari pihak swasta. Sayang, saya belum berhasil melacak nama dan bentuk korporasinya.
Di bagian akhir manifesto hanya tertulis: “Ketua // ttd // Tito Juniadi”. Ada
ketua, berarti pemiliknya lebih dari satu orang. Namun, mengapa ketua? Bukan
direktur atau manajer? Mungkinkah badan usahanya berbentuk koperasi? Atau, malah
hanya semacam paguyuban? Profil Tito Juniadi pun masih sulit diulik. Segelintir
media yang sempat menyebut namanya hanya memberikan atribusi “miliarder kelahiran
Pacitan yang berdomisili di Sukoharjo”.
Saya juga belum mendapat penjelasan tentang dua atribut yang
terpampang dengan huruf balok besar-besar: SATRIA ALAM dan PETANI HATI. Masing-masing
terbentang di lokasi terpisah. Apakah keduanya serangkai dan merupakan
nama badan usaha atau sekadar sepasang slogan yang mencerminkan ideologi
usahanya?
Ah, di tengah kesibukan mereka-reka tafsir atas dua frasa
itu, mata saya tergoda oleh label pada kertas HVS berlaminasi yang menempel pada
tunggak pohon. Saya mendekatinya. Tertulis begini: “DIJUAL!!! // PULE PURBA // Rp.
4M (4.000 jt)”. Saya duduk di depannya—agak ke samping—lalu berswafoto dengan
latar belakang tunggak termahal sedunia itu.
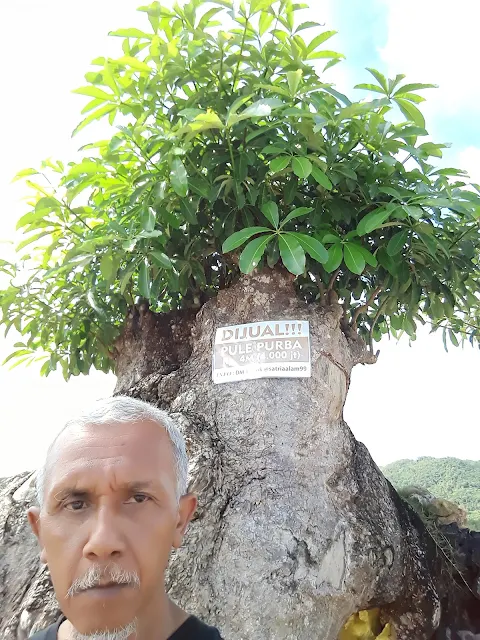 |
| Tunggak pohon termahal sedunia |
Saya terbengong: itu iklan serius atau bercanda? Hanya orang
gila yang rela merogoh deposito 4 miliar demi memboyong seonggok tunggak pulai—yang
oleh iklan itu diklaim sebagai pohon purba. Jangankan membeli, diberi gratis
saja saya tidak mau. Oleh masyarakat di dusun saya, pohon bernama Latin Alstonia
scholaris itu dipercaya sebagai hunian favorit bagi berbagai jenis makhluk
halus. Hiii, ... merinding!
Sejenak kemudian saya mencoba menerka-nerka maksudnya.
Dugaan saya, iklan itu sindiran belaka. Begini takwil saya atas iklan itu: mahar
semahal-mahalnya mesti dikenakan kepada sesiapa yang rakus dan semena-mena
terhadap alam! Alias, iklan bombastis itu menegaskan brand GD2 sebagai
kesatria penjaga kelestarian alam.
Angan saya lantas melayang ke wacana pro-kontra pendirian
pabrik semen di sekitar kampung halaman saya. Andai saja para pemangku
kepentingan dan kebijakan—konon mengatasnamakan demi kesejahteraan masyarakat Wonogiri selatan—sudi membaca fenomena GD2, tentu tidak perlu mengacak-acak
harmoni sosial-ekologis KBAK Gunung Sewu di Pracimantoro.
Pegunungan kapur di Sumur-Nujo terbukti
bisa disulap menjadi kebun alpukat sekaligus taman tamasya yang memikat—tanpa merusak
lingkungan alam dan sosial. Saya yakin, lanskap serupa di desa-desa sekitarnya
yang menjadi target penambangan bahan baku semen dan pendirian pabrik pengolahannya
itu pun bisa dikonversi menjadi area agrowisata yang produktif dan ramah lingkungan.
Di Praci sendiri, plus kecamatan-kecamatan tetangganya,
tidak sulit untuk menemukan saudagar sekaliber Pak Tito Juniadi. Pemerintah
tinggal mengambil peran sebagai fasilitator untuk mempertemukan kepentingan
investor, masyarakat, dan alam. Yang masih menjadi taruhan, syahwat apa yang diperjuangkan:
mendayagunakan dan memberdayakan atau memperdaya?!
Tabik.





Tidak ada komentar:
Posting Komentar